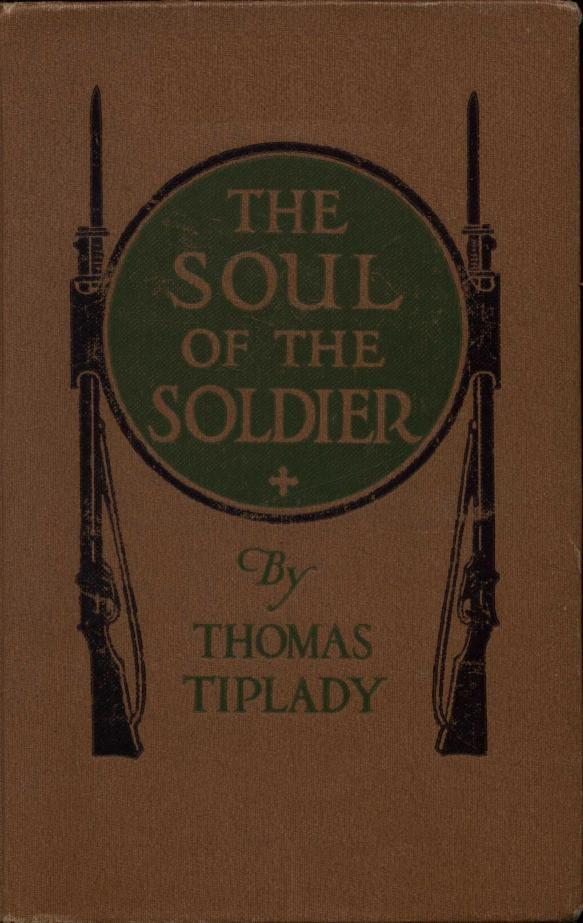|
| Sumber: www.hymntime.com |
Prolog: Ingatan, Janji, dan SalibDi antara lagu-lagu pujian yang saya tahu, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala adalah salah satu yang spesial. Dahulu nyanyian dari Kidung Jemaat No. 183 ini dibawakan oleh sekumpulan mahasiswa STT GKE di depan jemaat GKE Eben Ezer dalam ibadah Minggu. Barangkali sudah tradisi, mahasiswa baru kampus teologi di Banjarmasin itu memperkenalkan diri kepada jemaat melalui persembahan pujian. Saya remaja berusia 18 tahun, yang sebelumnya telah menulis janji, berada di antara muda-mudi yang tampil pagi itu. Berikut liriknya:
Menjulang nyata atas bukit kala
t’rang benderang salibMu, Tuhanku.
Dari sinarnya yang menyala-nyala
memancar kasih agung dan restu.
Seluruh umat insan menengadah
ke arah cahya kasih yang mesra.
Bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah.
Setelah tidak sedikit keputusan hidup diambil, sesekali terlintas kenangan saat berdiri menyanyikan iman seraya meyakini panggilan yang kala itu terasa pasti. Menjulang Nyata Atas Bukit Kala tidak hanya mengingatkan akan panggilan itu, tetapi juga Salib yang hingga kini masih saya imani. Cerita saya bukan pengalaman hidup-mati, tetapi jika seseorang dapat menunjukkan arti hidup-mati dan salib, orang itu salah satunya Thomas Tiplady, pengarang syair itu.
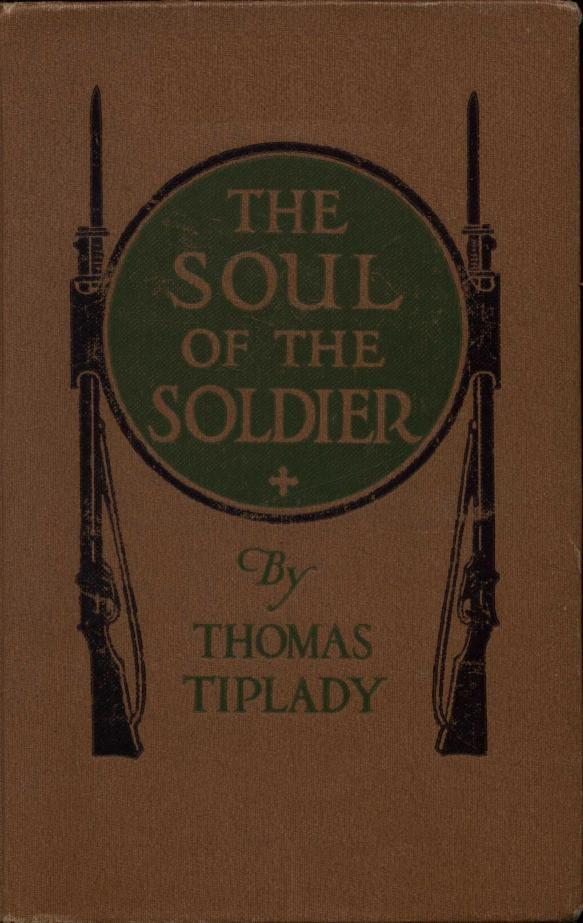 |
| Sumber: www.gutenberg.org |
The Soul of the Soldier: Kengerian Perang dan Salib MenjulangKidung terjemahan E. L. Pohan Shn aslinya berjudul
Above the Hills of Time. Thomas Tiplady (1882-1967), seorang pendeta Methodist, diketahui sebagai penulis syair ini. Akhir-akhir ini, saat media penuh dengan berita-berita perang dan kengerian lainnya, saya menemukan memoir Tiplady yang berjudul
The Soul of the Soldier: Sketches from the Western Battle-Front, yang terbit pada tahun 1918 (bisa dibaca di
laman ini). Buku ini berisi kisah beserta refleksinya berdasarkan pengalama melayani sebagai pendeta pasukan di Prancis pada Perang Dunia I. Tiplady memberi gambaran keadaan batin, karakter dan keteguhan para prajurit yang bertugas di Front Barat.
Serdadu-serdadu yang berjuang di medan tempur lebih terhormat daripada siapa pun. Mereka bersentuhan langsung dengan realitas hidup dan mati, tetapi semua justru membuat mereka lembut dan bermartabat. Berikut beberapa kutipan dari The Soul of the Soldier yang menggambarkan kengerian dan pergumulan bersama para serdadu.
Bahkan laut penuh dengan perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tidak bertempur, yang ditenggelamkan olehnya.
Pembuat jalan itu berbuat lebih banyak demi persaudaraan manusia dan perserikatan dunia daripada ahli pidato yang paling hebat sekalipun.
Tidak ada nyanyian patriotik di Front .... Mereka mengungkapkannya siang malam dengan bertahan terhadap kesusahan dan cedera.
Sukacita bisa bernyanyi dan Kesedihan bisa bernyanyi, tetapi Keputusasaan itu bisu.
Namun, izinkan saya membagikan perenungan Tiplady tentang Salib dalam bab berjudul The Cross at Neuve Chapelle. Diceritakan bahwa di Front Barat Prancis terpasang salib-salib di setiap persimpangan jalan utama. Tujuannya agar ketika menghadapi persimpangan jalan hidup, di tengah keraguan, para prajurit ingat bahwa mereka membutuhkan Juruselamat dan penebusan oleh kasih-Nya. Setiap waktu ada prajurit yang gugur di medan pertempuran, dipasanglah salib putih sederhana bertuliskan nama mereka. Menurut Tiplady, Salib Kristus membuat Kalvari mengemuka "mengatasi semua bukit yang lain dalam sejarah". Salib pula merupakan satu-satunya filosofi yang dapat diterima untuk menjelaskan realitas perang (the only acceptable philosophy of the war).
 |
Korp Ekspedisioner Portugal di depan Salib
Neuve Chapelle ketika masih utuh (1918) |
Para prajurit menggali parit perlindungan mereka melewati sebuah desa, Neuve Chapelle. Ketika para pasukan menghadapi musuh, persis di belakang mereka tanah luas terbuka dengan salib yang menjulang. Dengan tubuh Kristus terpaku di sana, salib di Neuve Chapelle itu merupakan pemandangan paling mengagumkan. Ketika pecah pertempuran di desa itu, selisih tiga tahun sebelum memoir Tiplady terbit, Kristus yang tersalib di sana menjadi refleksi persaudaraan lewat kematian. Ditulisnya bahwa ada kesatuan perasaan yang mistis antara parit itu dan Salib, antara serdadu dan Juruselamatnya.
Bagi serdadu Portugal yang turut dalam perang itu, pertempuran di Neuve Chapelle merupakan yang terhebat dan memilukan dalam sejarah mereka. Tidak disangkal, Salib di Neuve Chapelle itu juga saksi bisu kebiadaban. Tiplady menceritakan bagaimana salib-salib dimanipulasi oleh pihak yang menginginkan perang dan penderitaan. Akibatnya, semakin banyak pasukan berjatuhan. Demi ambisi salib dilucuti kesuciannya. Akhirnya, Salib Kristus dipahami sebagai penguji atau hakim terhadap tirani tersebut. Bab itu ditutup dengan kata-kata berikut:
Salib Kristus menjulang di atas segala yang hancur sepanjang zaman, dan akan sintaslah bangsa-bangsa yang berdiri di bawah lengan penjagaannya di parit perlindungan keadilan, kemerdekaan dan kebenaran.
Tiplady telah menunjukkan bahwa manusia membutuhkan Salib demi memahami maksud semua yang terjadi dalam perang yang tidak saja ngeri tetapi menghancurkan.
Above the Hills of Time: Salib sebagai Kenyataan Sejarah Paling UtamaTampaknya, kisah serta perenungan inilah yang melatarbelakangi syair karangan Tiplady yang telah lama saya kenal. Menurut
hymntime.com, kidung itu ditulis pada tahun 1931.
Above the hills of time the cross is gleaming,
Fair as the sun when night has turned to day;
And from it love’s pure light is richly streaming,
To cleanse the heart and banish sin away.
To this dear cross the eyes of men are turning,
Today as in the ages lost to sight;
And so for Thee, O Christ, men’s hearts are yearning,
As shipwrecked seamen yearn for morning light.
Mengetahui kisah di baliknya membuat syair ini semakin indah, tetapi juga dalam. E. L. Pohan Shn membuat terjemahan lagu ini dengan mutu dan keindahannya yang setara. Tidak mudah menerjemahkan syair puitis. Misalnya, "kasih agung dan restu" oleh Pohan memadatkan dua baris tentang cahaya suci kasih yang membersihkan hati dan membuang dosa.
Namun, sejujurnya, lama sekali ungkapan "bukit kala" (the hills of time) saya nyanyikan tanpa sungguh-sungguh memahami maknanya. Ternyata, membaca The Soul of the Soldier dan mencermati syair aslinya membantu menelusuri arti "bukit kala". Bukit kala atau zaman mengacu kepada bukit Kalvari yang mengatasi segala bukit sepanjang sejarah. Di sana Salib Kristus berdiri. Metafora zaman diulang kembali pada baris berbunyi "Today as in the ages lost to sight" (Hari ini seperti pada masa-masa yang telah hilang dari pandangan). Ini tidak muncul dalam terjemahan Indonesia, tetapi dibiarkan tersirat dalam frase ringkas "seluruh umat insan". Namun, sulit memungkiri bahwa metafora zaman itulah yang memberi struktur pada seluruh baitnya. "Above the hills of time" dan "today as in the ages lost to sight" menunjukkan makna pengurbanan Kristus dan kasih-Nya bagi setiap insan di sepanjang zaman. Bayangkan bukit yang menyimbolkan kekekalan dan salib menjulang di atasnya. Dalam The Soul of the Soldier, Tiplady menguraikan lebih lanjut:
Di hadapan kaki langit sejarah manusia, Salib berdiri dengan terang, dan segala yang lain tertutup bayangan. Salib-salib di pinggir jalan di Front dan kilatan senjata yang berderu mungkin tidak mengajarkan prajurit kami banyak sejarah, tetapi mengajarkan mereka kenyataan sejarah yang terutama.
Di antara desingan peluru, kelaparan dan kengerian-kengerian lain, tampaknya bukan senjata dan kekuatan yang dunia butuhkan. Dalam teologi Tiplady, hanya Salib yang menjelaskan wajah perang sesungguhnya. Sementara serdadu-serdadu gugur berlumuran darah, kekuatan dan kekuasaan tirani tidak mempedulikannya. Adakah bentuk kekuatan lain yang mengimbangi itu?
 |
Syair Bowring yang dimuat dalam
The English Hymn Book (1879) |
Kemungkinan Pengaruh Sir John BowringTentu saja perlu mencermati perbedaan dalam syair Above the Hills of Time dibandingkan dengan prosa reflektif Tiplady dalam The Soul of the Soldier. Kidungnya sarat dengan metafora cahaya. (gleaming, fair as the sun, turned to day, pure light, dan seterusnya). Ternyata ia bukan yang pertama menggunakan metafora ini. Sir John Bowring, diplomat Inggris yang juga penulis himne, menggambarkan kesucian Injil yang memancar agung di atas Salib dalam In the Cross of Christ I Glory (Salib Kristus Kubanggakan, KJ 394). Menurut The Complete Book of Hymns (2006), Bowring menulisnya karena terinspirasi oleh pemandangan salib di atas reruntuhan katedral di Makau, seolah-olah mengantisipasi pengalaman Tiplady.
Syair Bowring itu juga terilhami oleh kesaksian Paulus bahwa tidak ada alasan untuk bermegah kecuali salib (Gal 6:14). Sebagaimana ciri khas sastra Romantik di abad ke-19, Bowring mengangkat tema keterhubungan pengalaman lampau dengan kekinian (baca
di sini). Pengalaman Paulus juga merupakan pengalaman kita. Dari syair Bowring tersebut pula berasal ungkapan Salib "menjulang di atas reruntuhan kala" (
towering o'er the wrecks of time), yang juga digunakan oleh Tiplady untuk menerangkan Salib dalam prosanya.
Dalam memoirnya, perang yang tidak kunjung berakhir meletihkan raga dan jiwa. Dalam kidung, Tiplady menggunakan pelaut yang karam sebagai gambaran kondisi eksistensial sekaligus rohani. Tampaknya ia sedang merenungkan bentuk "peperangan" lain. Pergumulan ini juga meletihkan jiwa. Jika begitu, sewajarnya pandangan kita tertuju kepada sumber cahaya itu. Ia juga menjadi jangkar bagi kapal kehidupan, diombang-ambing tetapi tidak bergeser jauh.
Kedengarannya aneh memang, bukan yang kuat dan berkuasa yang memberi harapan. Tiplady menulis,
Hannibal, Cæsar, Napoleon—mereka mungkin berdiri di kaki bukit itu, seperti para prajurit Romawi, tetapi mereka tampak hina dan tidak berarti ketika Salib menjulang di atas mereka, menampakkan sosok sang Anak Manusia.
Salib di Kalvari itu, bagi Tiplady, sebagaimana keyakinan Bowring yang menginspirasi prosa dan puisinya, lebih mulia daripada kekuasaan atau kekuatan mana pun yang disaksikan sejarah.
Salib Itu Tetap Bercahaya
Ada kesempatan ketika begitu mudah menjumpai salib. Dahulu saya terbiasa melihatnya di ruang kuliah, kapel, gereja, bacaan, aksesori, dan sebagainya. Namun, ada waktu ketika pemandangan salib lebih sulit ditemui. Dalam pengalaman Tiplady, salib ditemukan di mana-mana, bahkan serdadu-serdadu terlatih untuk melihat perang itu sebagai salib. Bagaimana dengan tempat dan masa di mana gambar salib itu telah menjadi langka? Di mana bisa didapati lagi semacam pengingat akan pengurbanan sekaligus harapan itu?
Bagi tidak sedikit orang, salib itu tidak mudah terlihat. Mungkin terhalang oleh bangunan lain kehidupan. Seperti halnya melihat kenyataan perang dengan bantuan Tiplady, lebih baik daripada membayangkan sendiri dan membuat penilaian, melihat kenyataan hidup seutuhnya melalui salib menjadi penting. Apakah intuisi seseorang cukup terlatih untuk mengenalinya, di antara puing-puing reruntuhan dan wajah kelaparan, walau lambang salib itu tidak tampak? Nyatanya, kita tergoda untuk berharap pada kekuasaan. Namun, seperti dalam baris nyanyian Bowring, harapan menipu serta ketakutan terus mengganggu (Hopes deceive, and fears annoy).
Epilog: Antara Simbol dan Kenyataan
Ada apa dengan simbol sehingga kita harus hidup dengannya? Teschemacher, dikutip oleh Tiplady, mengisahkan kebiasaan pengelana gypsies yang memberitahu gypsies yang lain ke arah mana mereka pergi. Caranya dengan memetik rumput atau bunga, Patterain sebutannya, lalu menaburkannya di setiap persimpangan jalan. Salib-salib putih bagi serdadu serta memoir Tiplady sendiri memiliki fungsi seperti Patterain itu.
 |
Patung Yesus di Biara Portugal
di atas makam serdadu tak dikenal.
Sumber: www.bhsportugal.org |
Selain menyisakan reruntuhan, pertempuran di Neuve Chapelle meninggalkan tubuh patung Yesus sementara kayu salibnya hancur tak bersisa. Pemerintah Portugal membawa dan menaruhnya di Biara Santa Maria da Vitória, Batalha. Di sana, jasad Yesus yang tidak utuh lagi itu menjadi simbol (baca di sini). Menurut Mark Crathorne, tubuh Yesus itu tidak hanya melambangkan keberanian para serdadu, tetapi juga perasaan "ditinggalkan oleh pihak yang telah mengirim mereka untuk berperang demi suatu tujuan yang tidak dapat dimengerti oleh sebagian besar dari mereka."
Begitu juga, refleksi singkat ini turut menandai jalan-jalan personal yang dipilih, kendati salib-salib tidak lagi tampak begitu jelas. Saya mengaku tertawan oleh kesederhanaan perenungan Tiplady yang berdasar pada pengalaman langsung. Kesederhanaan itu, bukan kecanggihan teologis, yang membuatnya tepercaya.
Di setiap persimpangan jalan, dalam ketidakpastian, kelemahan serta pilihan-pilihan yang paling sulit, ketika diingat dan dikenali, cahaya Salib menyapu setiap sudut hati dan pikiran. Di balik apa yang terlihat oleh mata tersembunyi realitas dosa, kenyataan dasariah lintas masa. Itulah mengapa "kasih agung dan restu" itu teramat berarti. Saya harus mampu melihat kenyataan utama: Kristus mati bagi saya. Salib tidak serta-merta mengganti kenyataan yang kelam. Akan tetapi, tanpa Salib itu dunia menjadi terlalu kelam.